Stigma dan Tradisi: Berhenti Belajar! Mari Mulai Berpikir dan Menciptakan
16 Jun 2015 View : 4043 By : Niratisaya
“Agar sukses, kita harus melihat segalanya dengan pandangan unik kita sendiri. Dan tidak menelan mentah-mentah fakta yang disodorkan.”
Musim ujian sudah terlewati, terutama buat kamu yang berada di tahun terakhir jenjang pendidikan di sekolah. Tapi mari kita berusaha jujur, Artebianz; dari sekian banyak pelajaran yang kamu serap selama mengenyam pendidikan resmi, berapa yang menempel di kepala dan kamu praktikkan di kehidupan nyata? Bukan untuk sekadar dihafalkan dan demi mendapat rangking atau iming-iming, lho. Tapi benar-benar dipraktikkan. Berapa di antara kita yang benar-benar memahami pelajaran-pelajaran itu?
Dan pertanyaan yang paling mendasar, seberapa banyak pelajaran yang kita hafalkan itu membantu proses berpikir kita?
Saya memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut berulang kali setelah menonton sebuah video berjudul “Forget What You Know” dari akun TedxTeen dengan pembicara seorang anak yang divonis mengidap autism pada saat dia berusia 2 tahun. Dia bernama Jacob Barnett.
Jacob, yang pada saat berbicara di panggung TedxTeen, berusia 12 tahun. Tak jauh berbeda dari anak-anak yang mengidap autisme lainnya, dia menerima banyak cap dan “ramalan-ramalan” negatif dari orang-orang sekitar ketika gagal mengikuti pelajaran di sekolahnya (yang setingkat PAUD kalau di Indonesia) dan nggak mampu berkomunikasi dengan baik terhadap sekitarnya.
Namun, benarkah Jacob, dan anak-anak pengidap autisme lainnya, benar-benar nggak mampu berpikir dan berkomunikasi seperti yang selama ini tertanam dalam stigma masyarakat umum?
Sepuluh tahun semenjak menerima vonis dokter bahwa dia menerima vonis autisme yang akut, Jacob berdiri di panggung TedxTeen dan menceritakan seluruh pengalamannya selama dia dalam fase bungkam dan sibuk sendiri—yang lebih populer (dan salah sebut di Indonesia) dengan istilah autisme.
Baca juga: Foodiology TEDxTuguPahlawan, Ketika Makanan Lebih dari Sekadar Penahan Lapar
Belajar versus Berpikir
Sejatinya, ketika Jacob diam dan berdiri menatap cahaya bergantian dengan bayangannya (satu hal yang sering kali dilakukan Jacob sewaktu dia masih kecil), dia sedang berpikir tentang spectrum cahaya dan mengapa sinar bisa memantul serta menciptakan bayangan. Namun, karena Jacob terlalu serius dengan kegiatan individualnya ini dan sering tak mengacuhkan sekelilingnya, orang-orang tak menganggapnya sedang berpikir dan mempelajari alam sekitar.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian belajar adalah:
1. berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu;
2. berlatih;
3. berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman; pada kenyataannya.
KBBI nggak menyebutkan tentang keharusan untuk berada di dalam sebuah kelas, mempelajari sesuatu dari buku, dan segala yang ada dalam stigma masyarakat tentang belajar. Hanya tentang usaha untuk memperoleh kepandaian, latihan, dan ketanggapan seseorang atas pengalaman yang diperolehnya. Dengan kata lain, belajar bisa dilakukan di mana-mana dengan bantuan siapa saja.
Akan tetapi, pada kenyataannya kegiatan belajar dalam pemahaman tradisional masyarakat kita—juga kemungkinan besar dunia—adalah sebuah kegiatan yang melibatkan seorang guru yang mengajar, sebuah kelas, buku-buku, dan institusi formal. Walhasil, mereka yang memiliki “keistimewaan” seperti Jacob dan kawan-kawan dianggap sebagai produk gagal dan perlu “diservis” agar mesinnya, alias otaknya, bekerja dengan normal seperti kebanyakan dari kita.
Namun, seperti yang disodorkan oleh Jacob pada para peserta acara bincang-bincang TEDxTeen, apakah kita benar-benar belajar agar bisa berpikir?
Nggak.
Sebagian besar dari kita belajar dengan rajin karena terbawa arus program wajib belajar yang diganjarkan oleh pemerintah pada penduduknya. Sebagian lainnya karena harga diri: nama sekolah yang mentereng, jenjang pendidikan tinggi yang mampu mendominasi, dan lain-lain.
Namun, berapa banyak pelajar dari 250 juta penduduk Indonesia yang murni belajar karena mereka ingin mampu berpikir, memiliki tingkat kemawasan, serta kesigapan terhadap lingkungan dan alam?
Kebanyakan dari kita belajar di sekolah hanya demi memenuhi alat-alat pengukur yang ada demi bisa masuk ke dalam kategori pintar. Sehingga, pada akhirnya tujuan belajar bukan lagi kemampuan untuk memahami dan memikirkan sesuatu, tetapi lebih pada angka (rangking dan nilai). Yang kemungkinan besar membuat orang-orang terdorong untuk melakukan suap atau membayar pihak tertentu demi mendapatkan angka-angka memuaskan. Atau demi mendapatkan ijazah tanpa melakukan apa-apa.
 Gambar diambil dari edukasi.kompas.com
Gambar diambil dari edukasi.kompas.com
Jika tujuan mereka, baik penyedia jasa ijazah palsu dan pengguna jasa tersebut, semula adalah menciptakan masyarakat akademisi dengan kemampuan berpikir yang tajam, maka fenomena ijazah palsu nggak akan pernah terjadi. Dan nggak akan ada penutupan institusi pendidikan secara massal.
Menurut saya, modal utama dalam belajar adalah berpikir, jika seseorang sudah berhenti berpikir dalam proses pendidikannya, maka dia nggak bisa lagi dibilang belajar.
Berhenti Belajar!
Mari Mulai Berpikir dan Menciptakan
Salah satu ucapan Jacob yang menohok saya adalah ketika dia menyebut mengenai fakta bahwa sebagian besar dari kita lebih sering menerima fakta yang disodorkan pada kita—baik lewat guru maupun buku—alih-alih membuktikan kesahihan teori atau ilmu tersebut.
Jacob kemudian menyodorkan dua nama penting dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai pembanding, yang kedua-duanya terpaksa berhenti belajar, tapi tidak pernah berhenti berpikir. Yang pertama adalah Isaac Newton.
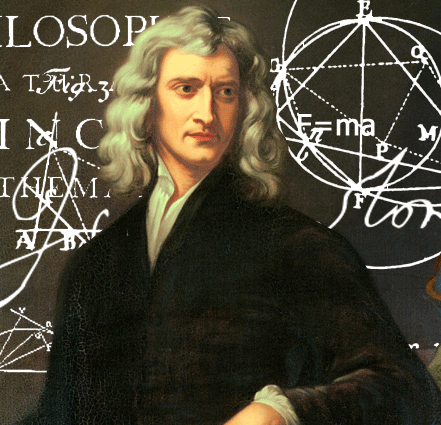 Gambar diambil dari gohistorygo.com
Gambar diambil dari gohistorygo.com
Pada tahun 1665, Newton berkuliah berkuliah di Cambridge. Namun sayangnya, wabah penyakit membuat universitas tersebut terpaksa tutup dan Newton kehilangan media untuk belajar. Nggak ada lagi dosen atau perpustakaan yang bisa dia ajak diskusi dan datangi. Newton pun terpaksa berhenti belajar.
Namun, Newton akhirnya sadar; meskipun nggak mempunyai kelas, guru maupun perpustakaan, bukan berarti dia harus berhenti berpikir. Justru dengan kehilangan media untuk belajar, Newton “dipaksa” oleh rasa penasarannya dan keadaan untuk terus berpikir. Dia mulai mengamati sekitar dan memikirkan fisika perbintangan dan pergerakan bulan mengelilingi bumi (revolusi) yang telah lama menarik perhatiannya.
Untuk membuktikan pikiran dan dugaannya, Newton kemudian menciptakan hal-hal yang mungkin pada waktu itu disebut gila: calculus, tiga hukum Newton—yang menjadi dasar mekanika klasik, hukum gravitasi, teleskop refleksi, dan benda-benda lain dalam kurun waktu dua tahun saat dia harus berhenti belajar.
Nah, bayangkan seandainya Newton nggak berhenti belajar. Oke, dengan kecerdasannya Newton bakal jadi mahasiswa yang baik—hebat mungkin malah. Tapi bisa jadi proses belajar Newton bakal mengganggu temuan dan cara berpikirnya. Selain itu, nggak akan ada hukum gravitasi, teleskop refleksi, dan kita masih berputar di dunia apatis yang berpikir semua sudah dari sononya, nggak perlu dipikirkan lagi.
Terima kasih pada wabah penyakit di tahun 1665, Newton pun mulai melihat dan berpikir dengan perspektif uniknya, kemudian menciptakan benda-benda hebat yang membantu kita sampai sekarang. Walaupun toh, ada teorinya yang dipatahkan oleh generasi berikutnya.
Generasi berikut tersebut adalah Albert Einstein, contoh kedua yang dipilih oleh Jacob.
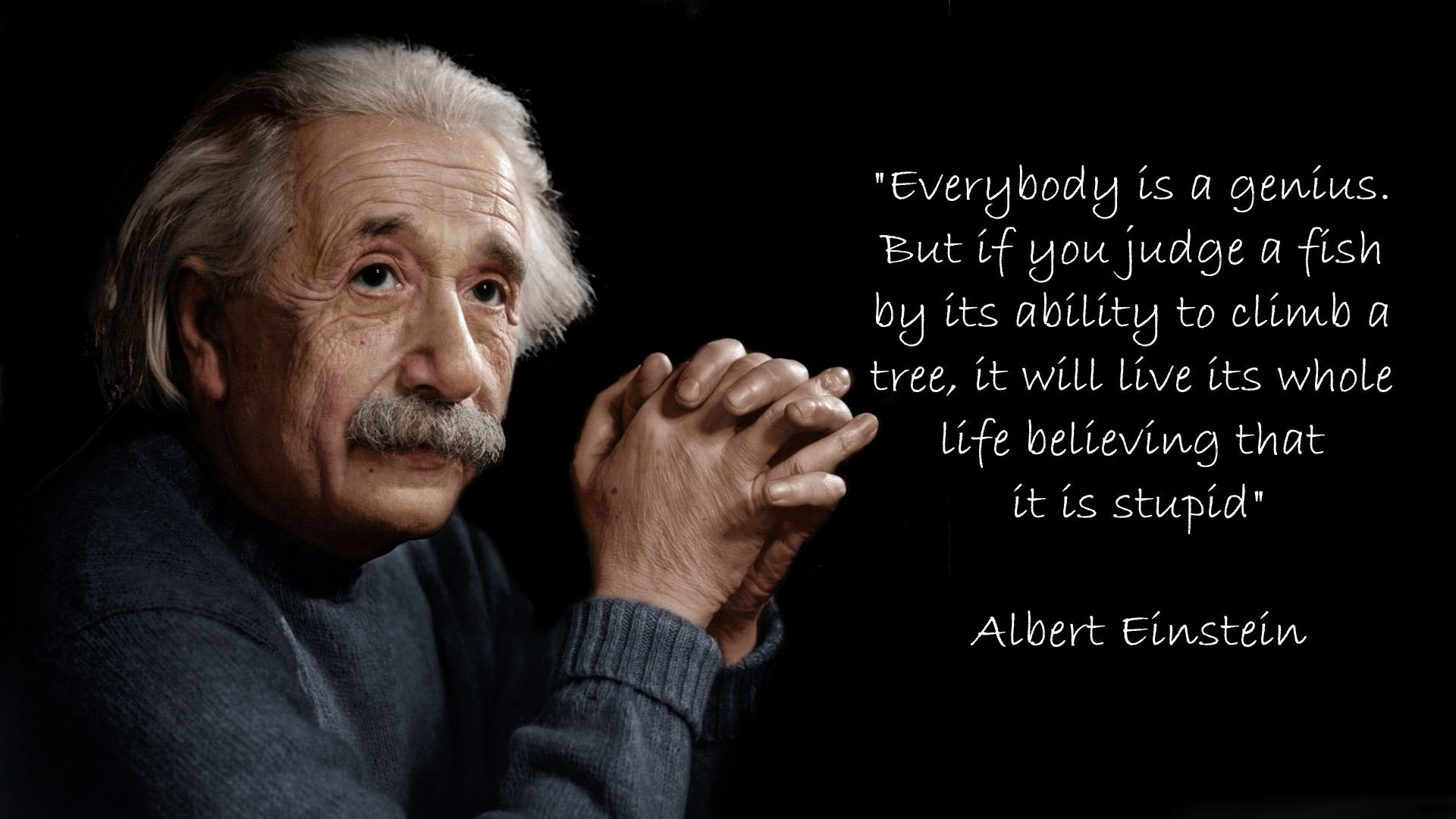 Gambar diambil dari reddit.com
Gambar diambil dari reddit.com
Berbeda dengan Newton yang harus berhenti belajar karena keadaan, Einstein harus berhenti belajar karena fakta bahwa dia adalah seorang Yahudi di Jerman. Einstein ditolah oleh universitas lokal dan dipaksa bekerja menjadi pegawai kantoran di perusahaan yang berurusan tentang hak paten, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan fisika. Tapi apakah ini menghentikan Einstein untuk berpikir?
Nggak.
Fakta bahwa dia nggak lagi bisa belajar (di sekolah) membuat Einstein memiliki banyak waktu untuk berpikir—lagian serius, Artebianz, ada berapa banyak urusan yang bisa diurus seorang pegawai di perusahaan hak paten di zaman NAZI berkuasa? Einstein lantas menggunakan waktu luangnya untuk berpikir dan berkhayal tentang gravitasi, yang kemudian saling berkaitan dengan hal-hal “gila” yang sama sekali nggak terpikirkan oleh para ilmuwan lainnya. Dan pikiran ini datang pada Einstein setelah dia membuang semua yang telah dipelajarinya di sekolah dan mulai berpikir dan menciptakan. Dia menemukan teori relativitas, efek fotolistrik, gerak brown, persamaan medan Einstein, dan lain-lain.
Dari kedua tokoh tersebut, Jacob menyimpulkan bahwa yang berperan secara esensial bukanlah di mana atau dari apa kita belajar. Yang terpenting adalah bagaimana dan dari sudut pandang mana kita berpikir.
Baca juga: The Imitation Game - Menginspirasi Banyak Orang Tentang Makna Perbedaan
Genius: Ambisi Masyarakat, Fakta, dan Stigma yang Ada
Lima belas tahun setelah vonis dokter, kini Jacob telah menjadi salah satu ahli fisika termuda di Amerika. Selain itu, Pemuda kelahiran 26 Mei tahun itu kerap diundang di acara-acara teve dan bertemu orang-orang terkenal. Apakah dia menganggap dirinya genius? Dengan rendah hati, pemuda yang memiliki IQ melebihi Einstein itu menyanggah anggapan masyarakat tersebut.
Jacob menjawab bahwa dia hanya fokus pada satu hal, yang kemudian membuatnya berada di posisinya sekarang.
Semua berawal dari keinginan Jacob untuk menguasai matematika dan mendalaminya. Dia pun mempelajari pelajaran matematika untuk tingkat SMA dan undergraduate (yang mungkin setingkat diploma kalau di Indonesia, tapi tolong koreksi saya kalau salah) dalam dua minggu. Walhasil, Jacob pun mendaftar ujian universitas di usianya yang baru 10 tahun!
Berita ini tentu saja mengejutkan orang-orang, sebab Jacob dianggap nggak mampu berbicara sejak dia 2 tahun.
Tapi, sebelum duduk di kelas bersama orang-orang yang dua kali usianya, Jacob harus menjalani wawancara. Sayangnya, dia gagal dan harus menunggu satu semester. Dan karena kita sedang membicarakan Jacob di sini Artebianz, nggak bisa belajar di universitas nggak menghentikan Jacob dari berpikir. Dia pun menemukan teori orisinal mengenai astrophysics (fisika perbintangan).

Gambar diambil dari thesundaytimes.co.uk
Jacob pun bercerita tentang rahasia kesuksesannya: “In order to succeed you have to look everything with your own unique perspective. And not accepting the straight facts.”
Memang ucapan Jacob lumayan menohok, tapi kalau kita mau jujur Artebianz, ucapan pemuda yang tengah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Perimeter Institute itu ada benarnya. Dalam proses pendidikan, khususnya yang berlaku di Indonesia, teknik yang lebih sering digunakan adalah penyodoran fakta yang telah ada (lewat dikte dan ceramah guru, lantas didorong dalam-dalam ke ingatan pelajar melalui ujian). Nggak banyak, setidaknya dari apa yang saya alami dan dengar, institusi yang mendorong siswanya untuk meragukan ilmu yang telah dibukukan dan berpikir secara mandiri. Sementara zaman semakin global, terutama dengan program Masyarakat Ekonomi Asia.
Apa kita akan terus membiarkan generasi muda Indonesia disuapi ilmu dan nggak pernah diajar untuk berpikir kritis, lalu menjadi konsumen tanpa benar-benar bisa bernas dalam keahliannya?
Jadi, mari berhenti berdebat tentang tingkat kegeniusan kita dan membandingkannya dengan orang-orang yang (dianggap) genius.
Ayo, fokus pada diri kita, passion yang kita punya dan kemampuan yang kita miliki.
Dan tentu saja, melupakan apa yang kita ketahui, mulai berpikir, dan mencipta.
Baca juga: Malaikat Tak Bersayap
Sumber foto header: ctvnews.ca
Niratisaya a.k.a Kuntari P. Januwarsi (KP Januwarsi) adalah Co-Founder Artebia yang juga seorang penulis, editor, dan penerjemah.
Profil Selengkapnya >>





































