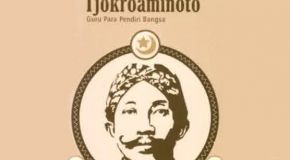Murni dan Tahun Baru
13 Jan 2016 View : 2221 By : Henny Kustanti
“Buku itu sulit dimengerti ya Uni? Dari tadi kok belum dibalik? Kalau kamu bantu saya sortir, saya kasih dah buku itu, biar bisa kamu baca di rumah.” Pak Ji pemilik salah satu toko buku bekas kesukaanku membuyarkan lamunanku. Pak Ji yang asli Jakarta, namun telah lama memilih hidup di Surabaya ini lebih suka memanggilku Uni. Katanya “terkesan lebih luwes”. Entah dari segi apa, mungkin dia hanya ingin kami lebih akrab.
Aku baru sadar sedari tadi belum beranjak dari halaman ini. Aku sedang teringat pembicaraanku dengan Ibu tadi siang.
“Setelah terima rapor besok liburan panjang tahun baru lho, Nduk,” kata Ibu sambil bikin adonan gethuk.
Aku terdiam dan merasa ndak perlu memberikan respons sama sekali.
“Biasanya teman-temanmu ngajak main ke mana-mana atau supping.”
Ibu bahkan kesulitan menyebutkan kata shopping. Pembicaraan semacam ini bukan milik kami. Aku merasa membodohi diri sendiri kalau harus menjawab Ibu.
“Kamu tahu kalung yang Ibu beli Lebaran lalu?”
Aku tahu arah pembicaraan ini. Menjadi remaja menjelang masa SMA yang katanya masa yang paling indah dan masa-masa terciptanya kesalahan menjadikanku lebih mempertanyakan banyak hal agar tetap waspada karena aku ndak ingin mudah terlena. Pembicaraan Ibu ini bukan ide yang bagus, sebaiknya dialihkan.
“Kata Pak Guru, Murni akan dapat beasiswa ke SMA Negeri setelah lolos tes, Bu. Murni mau konsentrasi belajar di rumah.” Sudah barang tentu aku harus belajar lebih keras dari teman-teman. Ini hukum yang ndak terbantahkan sebagai yatim yang juga tak kaya.
Sebenarnya aku sama sekali ndak keberatan, karena belajar memberi cap harga yang tinggi pada diriku. Teman-teman membutuhkan kepintaranku, meskipun aku tahu kedekatanku dengan teman-teman kadang terlihat begitu kaku dan palsu. Mereka malas mengajakku bermain kalau ndak ada PR atau tugas dari sekolah. Di belakangku mereka bilang aku gadis genius aneh yang lebih suka duduk di bangku paling belakang, tanpa kawan. Mereka ndak tahu aku lebih nyaman berperan sebagai penonton dan menyaksikan drama asyik teman-temanku yang menurutku lebih aneh dan konyol macam sinetron-sinetron tontonan favorit mereka hampir setiap sore. Dari kursi paling belakang itu juga aku tahu ketika mereka berbisik tentangku.

Menjadi penonton memberi banyak waktu untuk diriku sendiri melakukan hal-hal yang kusuka, seperti mengisi TTS di koran-koran bekas yang untuk selanjutnya dipakai Ibu sebagai wadah gethuk. Karena aku ndak memiliki banyak mainan, maka aku lebih senang nongkrong di Jalan Semarang untuk membaca buku-buku bekas. Sebagai gantinya, dengan suka hati aku membantu mereka menyortir buku di waktu luangku.
“Ibu tau kamu pasti akan rengking satu lagi seperti selalu, sejak kamu TK. Karena Ibu ndak pernah memberikan apa pun sebagai hadiah, kali ini Ibu ingin sekali. Tadi pagi Bu RT membeli kalung Ibu dengan harga yang lumayan, Ibu ndak rugi-rugi amat.”
Sudahlah Ibu, ini sudah sangat berlebihan, dan aku benci itu.
“Pak Guru bilang Murni pasti bisa lolos mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Tapi yang bikin Murni ragu adalah tes psikologinya. Murni belum pernah mengikuti tes itu, agak grogi juga.” Aku memaksa bibirku tersenyum sealami mungkin, akhirnya malah jadi terlalu lebar dan canggung. Aku sungguh ingin Ibu terpancing dan ‘memakan’ umpanku.
“Bu Sari bilang suaminya akan ngajak si sulung Siska dan teman-teman sekelasnya di kampung ini jalan-jalan ke Mentari Deb Kolektor.”
Maksud Ibu adalah Mentari Departemen Store, sekali lagi kegagalan pengucapan dan aku sudah merasa pembicaraan ini terlalu konyol. Saat-saat seperti ini adalah saat aku ingin tinggal di puncak gunung, di mana aku selalu merasa jadi diriku sendiri tanpa harus mendengarkan apa kata Pak ini dan Bu Itu. Kotak Pandora telah terbuka untuk diintip isinya.
“Tapi Murni ingat kata mutiara dalam sebuah film barat yang mengatakan ‘Seize the day’, untuk membantu Murni selalu siap meraih kesempatan yang datang.” Biasanya kata-kata berbahasa Inggris selalu menarik perhatian Ibu untuk kembali berpijak pada bumi. Aku yang ndak akan bisa duduk di bangku SMP tanpa beasiswa, dan ibuku yang seorang penjual gethuk keliling. Bukankah sebuah penghormatan tertinggi kalau Pak Ini dan Bu Itu menganggap kami selevel dengan mereka, serta mengaggap tiada kesenjangan ekonomi kami yang begitu kentara? Bukankah seharusnya aku setidaknya sedikit pura-pura bahagia?
Tetapi, betapa sulitnya kami hidup bersandingan dengan mereka yang memiliki segala adalah nyata. Persahabatan ini mau ndak mau memaksa kami bekerja seperti sapi perah hanya demi satu kata terkutuk yang disebut “citra”. Sialnya, hal ini sama sekali ndak sanggup membuat kami bahagia. Kami justru terlihat semakin menyedihkan dalam upaya kami yang begitu keras untuk terlihat sama.
“Siska dan keluarganya adalah orang-orang yang baik. Kamu harus bergaul dengan orang seperti mereka Nduk, biar besok dapat suami seperti bapaknya Siska.”
Aku tahu pasti, maksud Ibu adalah Siska dan keluarganya adalah orang-orang yang kaya. Aku harus bergaul dengan orang seperti mereka “biar besok dapat suami kaya seperti bapaknya siska”. Ibu ndak tahu aku lebih keras kepala dari yang Ibu sangka.
“Nanti kalau Murni berhasil masuk SMA Negeri, artinya Murni semakin dekat dengan cita-cita Murni selama ini, Bu.” Mimpiku adalah alasanku tetap bertahan dan ingin menjadi yang terbaik. Meskipun saat membawa pulang kembali gethuk-gethuk kami dari warung di malam hari adalah saat yang begitu rentan keputusasaan. Aku menyatakan dengan tegas penolakanku atas itu. Hanya berpikir tentang mimpiku menjadi pemilik sebuah sekolah untuk anak-anak ndak mampu tapi berprestasi saja, telah membawaku menjadi lebih kuat dan tahan banting. Namun Ibu menghianati mimpiku dengan ndak memercayai kemampuanku akan bersinar tanpa bantuan ‘sahabat-sahabat’ kami.
“Uang dari menjual kalung bisa—”
“Murni sangat percaya bisa lolos tes masuk, Bu. Ibu percaya Murni, kan?” Tolong Bu, dadaku sesak. Pawonan yang ndak terlalu luas ini terasa semakin mengimpit. Kami telah lari terengah-engah sepanjang hidup kami hanya untuk menjadi lebih pantas hidup harmonis dengan para kaum yang melabeli diri mereka dengan sebutan modernis di sekitar kami. Aku sungguh ingin berhenti berlari. Pelarian ini seringkali membuatku kehilangan rasa nikmat yang harus manusia rasakan selama hidup. Dan aku merasa sendiri, terpuruk, tersungkur.
“Hush! Kamu ini Nduk. Ndak baik menyela pembicaraan orangtua. Ah, ibu sampai lupa mau ngomong apa. Wes, yang penting kamu ndak usah kuatir tentang kalung itu. Ibu juga ndak terlalu suka modelnya.”
Ibu selalu begini untuk menenangkan hatiku, dan aku semakin merasa buruk. Ini adalah salahku. Adalah salahku ketika kami ndak memiliki pilihan hiburan yang lebih baik dari televisi. Televisi 19 inci yang ketika pertama dinyalakan layarnya hanya mampu menunjukkan gambar yang ndak penuh, sehingga orang-orang di dalamnya juga terlihat seperti kurcaci di dongeng Snow White dan membutuhkan waktu setidaknya satu hingga dua jam sebelum dia benar-benar dapat menampilkan performa terbaiknya.
Adalah salahku ketika Ibu pada akhirnya begitu terbuai dengan apa pun yang disuguhkan tayangan di televisi hingga suatu hari tercetus, “Kita harus beli itu, Nduk. Katanya membawa kabar gembira.” Ingar-bingar dunia pertelevisian membuat setiap tampilannya tampak meyakinkan dan begitu nyata. Adalah salahku ketika Ibu menganggap setiap yang dilakukan Ibu-Ibu di sekitar kami pada rambut, tubuh, pakaian bahkan rumah mereka benar adanya. Ibu jadi merasa perlu membeli AC untuk rumah kami yang hanya sedikit lebih luas dari kamar kos-kosan mahasiswa Surabaya. Aku membutuhkan waktu hingga beberapa hari untuk meyakinkan Ibu yang sebaliknya.
Meyakinkan ibu-ibu yang lapar beli ini-itu yang ndak perlu, sama sekali bukan perkara mudah, Kawan.
Tentu saja, ini juga salahku ketika Ibu menginginkan yang terbaik bagi buah hatinya untuk menghabiskan liburan dengan segala kebiasaan dan budaya yang mengikutinya, sehingga merasa perlu menjual kalung. Yang hanya dimilikinya ndak lebih dari enam bulan. Ingatan atas betapa berbinarnya mata kecil Ibu ketika ia membeli kalung itu pun belum ingin hilang. Ibu mematut dirinya begitu lama di depan cermin kecil yang hanya memantulkan wajahnya yang sudah ndak muda lagi. Aku ragu ia dapat benar-benar melihat pantulan kalungnya di cermin.
Pada saat itu aku pikir betapa sederhananya membuat Ibu bahagia. Kalung dengan liontin berbentuk bunga dengan batu intan kecil di tengahnya itu bahkan ndak sebanding dengan kalung yang biasa dipakai ibu-ibu tetangga ke pasar saking kecilnya, dan Ibu hanya memakainya ketika lebaran. Seakan kalung itu adalah benda paling berharga yang pernah dimilikinya. Betapa sakit hatinya harus melepas kalung itu di tangan Bu RT yang ndak lama lagi tentu akan menggantinya dengan kalung yang lebih besar agar kelihatan bersinar bahkan dari radius 100 meter.
“Murni ndak pengen liburan ke mana-mana Bu.” Aku menyerah, demi setitik air menggenang di ujung matanya.
“Murni mau bikin donat untuk dijual Bu, kita bisa dapat untung lebih besar untuk beli kalung Ibu lagi. Murni ndak bisa melakukan apapun untuk Ibu selain berusaha yang terbaik untuk bikin Ibu bahagia.”
Aku ndak bisa lebih lama menghadapi Ibu, maka aku segera beranjak pergi hanya sesaat sebelum air mata itu benar-benar menyerah pada gravitasi bumi. Gethuk hari ini sedikit terlambat diantar.
Aku benci diriku sendiri karena membuat Ibu menangis. Aku benci diriku sendiri karena mengetahui bahwa ada setitik bagian dari hatiku yang menginginkan liburan itu. Pikiran ini mampu menonjok ulu hati hingga sumsum tulang belakang. Sakit, sungguh.
“Saya bantu besok Pak Ji, bukunya saya bawa pulang besok juga.” Aku berjalan sedikit tergesa, setengah berlari. Aku akan mengingat rasa sakit ini seumur hidupku. Tapi aku sudah memutuskan rasa sakit ini ndak akan datang lagi, karena aku lebih persisten dari patung Bung Tomo.
Wanita yang begitu ingin membahagiakan aku ini masih di pawonan, membelakangiku. Napasku terengah.
“Apakah Ibu bisa senang hanya dengan Murni dan apa yang kita punya?”
Ibu berhenti meniup bara dari lubang bambu.
“Karena Murni bahagia Bu, Murni memiliki mimpi yang akan Murni capai. Murni akan belikan Ibu kalung yang cantik.” Aku memeluk Ibu dari belakang.
Aku tahu kami akan baik-baik saja. Aku tahu aku akan baik-baik saja, karena aku menemukan makna Tahun Baru yang lebih berharga dari intan permata.
Henny Kustanti adalah seorang ibu rumah tangga yang menyaru sebagai Youtuber paruh waktu, sekaligus foodie alim.
Profil Selengkapnya >>