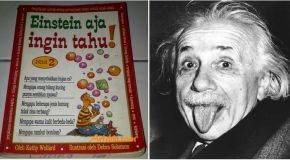Sebuah Wajah, Sebuah Rasa (Bagian Enam)
14 Jul 2015 View : 3464 By : Niratisaya
Pastikan membaca sub-bab "Sebuah Wajah, Sebuah Rasa" sebelumnya:
- Sebuah Wajah, Sebuah Rasa (Bagian Pertama)
- Sebuah Wajah, Sebuah Rasa (Bagian Kedua)
- Sebuah Wajah, Sebuah Rasa (Bagian Ketiga)
- Sebuah Wajah, Sebuah Rasa (Bagian Empat)
- Sebuah Wajah, Sebuah Rasa (Bagian Lima)
6. Rasa yang Terkadang Harus Disampaikan Lewat Kata
Aku memandang ruangan di depan mataku dan mengerjap ketika mendapati interiornya.
“Ayo kita pergi Nobu-chan,” ajakku begitu kami berada di depan tempat yang kami tuju.
Nobuko menoleh dan mengernyit. “Kita baru saja sampai.”
“Aku tahu. Ayo kita pergi,” ujarku dengan keras kepala, membuat Nobuko membalikkan seluruh badannya dan menatapku penuh tanya.
“Aku tidak akan pergi sampai kau menjelaskan apa yang terjadi. Kenapa kita harus pergi?”
Karena aku benci perpaduan warna hitam-putih dan bentuk persegi, batinku. Namun aku tak mengatakannya pada Nobuko. Aku sadar betapa konyol dan kekanakannya alasanku itu—dan aku hafal benar bagaimana temanku itu akan bereaksi.
Saat ini kami sedang berdiri di depan sebuah kedai kecil yang nasi kari. Aku tidak berlebihan ketika mengatakan kedai itu kecil, karena tempat itu terletak di sebuah gang dan hanya seukuran 4 x 3 meter. Tapi itu bukan alasan mengapa aku tidak menyukai tempat itu. Aku tidak keberatan makan di tempat yang mungkin kalau di Indonesia sekelas warung tegal itu. Aku hanya tidak menyukai warna dan bentuk lantai kedai itu.
Ya. Warna dan bentuk lantai kedai itu adalah hitam-putih dan persegi.
Mengapa aku benci pada perpaduan pola itu?
Ini karena pola itu mengingatkanku pada papan catur dan betapa menjengkelkannya permainan itu. Aku benci bahwa untuk memainkannya, aku harus mengingat bidak apa bisa melangkah ke mana—memikirkan strategi yang mesti kulancarkan dan akan dilancarkan lawanku. Benar-benar melelahkan dan merepotkan. Lebih mudah memainkan othello. Atau ular tangga.
Dan kini, ada alasan satu lagi kenapa aku membenci catur: Kawabata Haruto.
Seperti catur, hubunganku dengan Kawabata Haruto pasca-kalimat “Sementara aku berusaha memahami perasaan asing yang kurasakan dan terbiasa dengannya, bisakah kita bersikap biasa saja?” yang diucapkannya lima hari yang lalu terasa rumit. Aku bagai sebuah pion yang berdiri di salah satu kotak permainan catur dan sedang kebingungan, ke mana aku harus melompat. Pada saat yang bersaman, aku juga ingin segera bergerak untuk mengetahui bagaimana Kawabata Haruto akan beraksi.

Dan, untuk menjelaskan hubungan penyebab kenapa aku tak mau masuk ke kedai kari pada Nobuko…. Aku menggeleng secara mental sembari menatap wajah temanku. “Aku akan mentraktirmu makan di tempat lain.”
“Traktir?” tanya Nobuko dengan nada tak percaya sambil menatapku lurus-lurus, sebelum kemudian bersedekap. “Sepertinya ada yang mencurigakan di sini.”
“Apanya yang mencurigakan?” Aku balas bertanya sambil tertawa, yang sayangnya terdengar sumbang karena aku ingin bergegas meninggalkan kedai kari itu dan mengalihkan perhatianku dari tegel hitam-putihnya. Dari sosok Kawabata Haruto. Aku berbalik dan melangkah. “Ayo.”
Biasanya Nobuko akan segera mengejar langkahku, tapi ketika aku menoleh ke sebelahku, aku hanya mendapati udara kosong. Nobuko masih berdiri di depan kedai kari dengan tangan bersedekap, meminta penjelasan dengan ekspresi wajah cemberutnya dan suara “tap,tap” sepatu hak tingginya yang beradu dengan lantai semen jalanan.
“Bagaimana kalau kita membungkusnya dan makan di asrama?” tawarku.
“Dan kau harus menceritakan penyebab keanehanmu ini,” timpal Nobuko.
“Baik,” jawabku, mengalah. “Asal kau yang masuk dan mengantre untuk kita berdua.”
“Setuju,” balas Nobuko sambil melangkah riang dan ringan menuju kedai kari.
Melihat punggung Nobuko, aku tidak mengerti kenapa dia mengambil jurusan Sastra dan bukannya Hukum. Aku yakin dia akan menjadi pengacara atau jaksa yang hebat kelak.
***
Dua piring putih dengan bercak kecokelatan sisa bumbu kari tergeletak di atas meja bersama dua mug yang tadinya berisi teh hijau, sementara di hadapanku, Nobuko menatapku lurus-lurus dengan pandangan tak percaya.
Lima belas menit yang lalu, sembari menyantap kari pedas yang sudah lama kami inginkan, aku menceritakan penyebab aku menolak makan di kedai kari incaran kami. Hasilnya, seperti yang aku katakan sebelumnya: Nobuko menatapku tak percaya.
Aku menuang kembali teh hijau ke mugku, menunggu reaksi Nobuko.
“Ini konyol,” ucap Nobuko.
Aku meneguk tehku dan mengangguk. “Aku tahu.” Aku sudah tahu, sungguh. Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak kabur dari kedai itu.
“Aku kasihan pada Haruto-san. Dia harus ikut jadi aneh gara-gara dirimu.”
Alisku sontak bertaut mendengar ucapan Nobuko. Aku meletakkan mug tehku di sebelah mug Nobuko. “Hei, di sini akulah yang mestinya dapat simpati, bukannya Kawabata Haruto. Kau tahu kan apa yang dikatakannya padaku?”
Aku sudah menceritakan semuanya pada Nobuko tentang percakapanku dengan Kawabata Haruto, termasuk kalimat yang selama berhari-hari ini berenang-renang di kepalaku, tapi enggan aku katakan sekali lagi pada Nobuko.
“Memangnya itu gara-gara siapa?”
“Kau mau bilang ini gara-gara aku?” Aku sedikit naik pitam mendengar kata-kata Nobuko.
“Memangnya siapa lagi? Kau yang bersikap pasif. Kau tidak menerimanya, tapi kau juga tidak menolaknya. Siapa yang bisa menyalahkannya kalau dia bilang dia ingin kalian seperti dulu—sebelum dia menyatakan perasaannya padamu.”
“Kalau begitu kenapa dia nggak berusaha mendekatiku lebih serius?!”
“Bukannya kau yang membuatnya begitu? Kau sering memberi jarak pada semua laki-laki yang mendekatimu, memangnya apa yang kau harapkan dari Haruto-san? Dia juga laki-laki.”
Ucapan Nobuko membuatku terdiam. Meski ini bukan pertama kalinya Nobuko mengatakan tentang kebiasaanku itu, tapi aku masih merasakan rasa pahit dan sakit bagai hatiku dicubit.
“Apa yang sebenarnya membuatmu begitu, Indi-chan? Padahal sewaktu kau dan Haruto-san tidak bertemu, kau gelisah setengah mati—kau bahkan mematikan ponselmu. Kau tidak pernah begini sebelumnya.” Nobuko bertanya sambil bertopang dagu. “Kau menyukainya, kan?”
Nobuko menyorongkan tubuhnya ke depan. “Tidak. Kau bukan cuma menyukai Haruto-san. Kau… mencintainya?!” tebak Nobuko.
“Jangan macam-macam.” Aku meraih piring Nobuko dan menumpuknya di atas piringku, meraih mug kami, lalu membawanya ke bak cuci piring.
“Demi Tuhan, Indi-chan, apa susahnya mengatakan ‘ya, aku menyukainya’, atau ‘tidak, aku tidak menyukainya’?”
Aku mendengarkan omelan Nobuko sambil mencuci piring dan mug. Suara gadis itu beradu dengan suara air keran dan pikiranku.
Memang, akan lebih mudah kalau aku mengatakan perasaanku dengan jelas seperti yang dikatakan Nobuko. Tapi permasalahannya adalah aku sendiri tidak tahu apa yang kurasakan pada Kawabata Haruto. Atau mungkin… aku takut dengan apa yang aku rasakan serta apa yang terjadi pada kami kelak.
Gerakan tanganku sontak berhenti begitu pikiranku melontarkan satu kata itu.
Kami. Rasanya kata itu tidak tepat kalau digunakan untuk aku dan Kawabata Haruto.
“Hei, katakan padaku, kenapa kau tidak mengatakan saja perasaanmu pada Haruto-san?”
Aku tersentak saat melihat Nobuko yang tiba-tiba saja ada di sebelahku.
Aku terdiam. Ya, kenapa aku tidak mengatakan perasaanku pada Haruto-san? Aku meninggalkan piring dan mug, serta Nobuko yang tersenyum kecil melihatku terburu-buru meninggalkan kamar asrama kami.
Aku masih tak tahu tentang perasaanku pada Kawabata Haruto—apakah rasa yang membuatku gelisah ini bisa dilabeli dengan suka atau cinta, seperti yang dikatakan oleh Nobuko. Atau apakah ini sekadar kegelisahan karena orang asing, yang kemudian menjadi temanku, tiba-tiba merangsek maju dan menginginkan sesuatu yang lebih dariku.
Aku memejamkan mata sesaat sebelum keluar dari kamar. Kuhafal satu per satu detail wajah Kawabata Haruto, kemudian kuraba rasa yang ada di dalam dadaku. Tapi, hingga pintu kamar terbuka, aku tak menemukan jawabannya. Mungkin, aku akan menemukan jawabannya saat bertemu dengan Kawabata Haruto nanti.
***
Empat puluh lima menit dan satu setengah kaleng kopi instan kemudian, aku menemukan diriku di tangga depan apartemen Kawabata Haruto. Biasanya, lelaki itu sudah ada di rumah pada jam-jam ini. Tapi sepertinya hari ini dia terlambat. Ini mungkin karena hari ini adalah Jumat dan Chiba sedang dipenuhi oleh para turis. Atau mungkin Kawabata Haruto sedang menghabiskan waktunya di sebuah bar selepas kerja, layaknya para pegawai kantoran Jepang pada umumnya.
Atau mungkin dia sedang menghabiskan waktunya dengan Iwata Eriko.

(gambar diambil dari mamattew.devianart.com)
“Indi-chan?”
Ketika kepalaku menyajikan gambaran Kawabata Haruto dan mantan kekasihnya, pada saat yang sama, Kawabata Haruto muncul dengan setelan jas—minus dasi yang sepertinya sudah dilepasnya. Samar, aku mencium aroma sake dari tubuhnya. Ini berarti dugaan kedua benar; Kawabata Haruto baru saja pulang dari acara minum-minum dengan teman kantornya.
“Hai….” Aku tersenyum canggung.
“Kenapa kau ada di sini?” Tadinya aku mengira Kawabata Haruto akan melontarkan pertanyaan itu. Tapi tidak. Mula-mula dia berjalan menghampiriku tanpa berkata sepatah kata. Dia lantas berjongkok dan bertanya, “Kau sudah lama di sini?”
Wajah itu. Wajah polos dengan ekspresi khawatir itu entah mengapa membuatku ingin melayangkan pukulan. Aku membuang muka. “Lumayan.”
“Ada apa? Apa ada sesuatu?”
Aku terdiam, lalu menggeleng. Dan sejurus kemudian mengangguk.
Kemudian, terdengar suara Kawabata Haruto yang tertawa terkekeh-kekeh, sebelum kemudian dia duduk di sebelahku, meletakkan tas kerjanya di anak tangga bawah, lalu memangku jasnya yang sebelumnya dia lipat rapi.
“Kau ingat kan acara makan bersama kita dipindah di hari Minggu karena hari ini aku ada rapat?” tanya Kawabata Haruto nyaris mengeja tiap kata, seolah-olah dia sedang berbicara dengan anak kecil.
“Aku ingat.”
“Lalu, kenapa kau ada di sini?”
“Kau ingat apa yang kau katakan padaku sebelum kita ke La Cucina Hana?”
Kawabata Haruto terdiam beberapa saat—kedua alisnya yang mengingatkanku pada ulat bulu bertaut. Dia kemudian mengangguk dan membuka mulut. Tapi sebelum dia sempat mengeluarkan sepatah kata, aku mengangkat tangan dan menghentikan apa pun yang akan dikatakan oleh Kawabata Haruto.
“Jangan berkata apa-apa. Aku ingin kau mendengarkan apa yang aku katakan lebih dulu,” kataku. Tanpa menoleh pada lelaki di sampingku, aku tahu dia mengangguk. Aku bisa merasakannya. Tapi meski berkata demikian, aku tak tahu dari mana aku harus memulainya.
Aku menoleh dan mencuri pandang ke arah Kawabata Haruto. Dia masih dalam posisi yang sama: menatap lurus ke arahku. Aku pun kontan kembali menatap ke depan. Ke arah jalanan yang lengang.
“Tentang kata-katamu waktu itu….” Aku menarik napas. “Aku… sejujurnya aku tidak mempunyai jawaban yang kau inginkan.”
Aku terdiam, mengikuti suasana hati Kawabata Haruto. Tapi hingga beberapa menit aku menunggu, Kawabata Haruto masih terdiam. Sikapnya ini membuatku teringat pada permainan catur.
“Bu, bukan berarti aku menolakmu.”
Kawabata Haruto menoleh dan kedua sudut bibirnya terangkat.
“Bukan berarti kalau aku menerimamu juga!” aku buru-buru berkata demi menghapus cengiran di wajah Kawabata Haruto. Aku pun mengatakan apa yang ingin kukatakan pada Nobuko, juga pada semua lelaki yang dekat denganku tapi tak bisa.
“Aku tidak punya jawaban yang kau inginkan, karena aku sendiri tidak punya kepercayaan diri untuk berkata apakah aku punya perasaan yang sama denganmu, atau keberanian untuk menolakmu… karena aku tidak bisa menjauh darimu.” Aku menoleh dan kembali mendapati Kawabata Haruto yang menatapku intens. “Apa ini cinta? Aku… tidak bisa mengatakannya…. Maaf.”
“Mendengar seorang Indi-chan yang biasanya keras kepala meminta maaf, rasanya benar-benar aneh. Seperti berada dalam mimpi.” Kawabata Haruto berkata sambil tertawa.
Mendengar itu, aku spontan melempar tatapan menusuk pada Kawabata Haruto. Memangnya selama ini aku bersikap kurang ajar padanya, sampai-sampai dia bicara seperti itu?
Kawabata Haruto kembali tergelak saat dia melihat ekspresi wajahku. “Jangan memasang wajah begitu, Nona Pemarah,” katanya sambil menyebutkan nama panggilan yang dia gunakan dulu, sewaktu kami pertama kali bertemu.
Baru saja aku akan membuka mulut, bersiap menyemprot lelaki dengan tahi lalat di hidung ini, ketika dia tiba-tiba saja mengulurkan tangan. Bukan untuk menutup mulutku, tapi mengelus kepalaku.
“Kau mungkin mengatakan kalau kau bukan anak kecil, tapi apa yang kau katakan tadi membuktikan sebaliknya.”
“Apa maksudmu?”
Alih-alih menjawab pertanyaanku, Kawabata Haruto malah berkata, “Apa kita perlu mendefinisikan satu hal dan memasukkannya ke dalam kotak—seperti sampah, sementara kita tahu pasti kalau kita tidak bisa membuangnya? Kalau kau tidak bisa memberikan jawaban pasti… kalau kau merasa nyaman denganku, bagaimana kalau kita menerima satu sama lain dan biarkan semuanya mengalir?”
“Maksudmu, sama seperti hubunganmu dengan Iwata-san?” Aku mengerjap, antara takjub dan keheranan dengan solusi yang ditawarkan Kawabata Haruto.
Kawabata Haruto menggeleng. “Ini akan berbeda—benar-benar beda, karena aku tahu bagaimana perasaanku.” Dia meraih kedua tanganku dan meletakkannya di atas pangkuannya, di atas jas yang dilipatnya. “Jadi, bisa kita memulai segalanya, kali ini dengan dirimu yang mengingat apa yang aku rasakan dan diriku yang memahami kau belum mengerti apa yang kau rasakan?”
Aku menarik napas dalam-dalam sembari menatap Kawabata Haruto.
“Aku….”
Bersambung ke Sebuah Wajah, Sebuah Rasa (Bagian Tujuh)
gambar header diambil dari wallpaperseries.com
Niratisaya a.k.a Kuntari P. Januwarsi (KP Januwarsi) adalah Co-Founder Artebia yang juga seorang penulis, editor, dan penerjemah.
Profil Selengkapnya >>